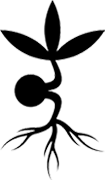Sebuah koperasi di Swiss mengembangkan sistem produksi pertanian yang didukung konsumen dengan membayar di muka. Konsumen juga diwajibkan bekerja di atas lahan beberapa jam per tahun.
Sebuah koperasi di Swiss mengembangkan sistem produksi pertanian yang didukung konsumen dengan membayar di muka. Konsumen juga diwajibkan bekerja di atas lahan beberapa jam per tahun.
Tanah seluas dua setengah hektar di kawasan Ziplo, Jenewa itu sepi. Hanya ada selada-selada kecil dan beberapa tanaman herbal. Karena masih transisi dari musim dingin ke musim semi di Swiss, aktivitas di koperasi Jardin du Chorroton pun masih lengang.
 “Ini bukan tanah milik petani dan konsumen di sini,” ujar Irene (29) enteng. “Empat tahun lalu, kami mengambilnya karena ditelantarkan,” kata dia lagi. Alkisah, tanah ini dulunya ditanami ala pertanian konvensional lengkap dengan pupuk dan racun kimia. “Pertanian di sebelah pun masih konvensional, ini (menunjuk batas tanah antara kedua lahan) adalah perbedaan antara kematian dan kehidupan.”
“Ini bukan tanah milik petani dan konsumen di sini,” ujar Irene (29) enteng. “Empat tahun lalu, kami mengambilnya karena ditelantarkan,” kata dia lagi. Alkisah, tanah ini dulunya ditanami ala pertanian konvensional lengkap dengan pupuk dan racun kimia. “Pertanian di sebelah pun masih konvensional, ini (menunjuk batas tanah antara kedua lahan) adalah perbedaan antara kematian dan kehidupan.”
Tanah pertanian di sebelah Jardin du Chorroton dimiliki pekerja imigran dari Portugal. Berbeda dari tanah yang dikelola Irene, tanahnya kelihatan sangat kering dan gersang.
Ada 140 keluarga yang menjadi anggota koperasi di bawah Uniterre, organisasi petani anggota La Via Campesina ini. Pada tahun 2007, mereka sepakat membuat koperasi dengan petani yang bekerja di lahan tersebut dengan model pertanian yang didukung konsumen (consumer supported agriculture).
 Uniknya dari sistem ini adalah konsumen membayar di muka sebesar 1.400 Franc Swiss (sekitar Rp13,2 juta) per tahun. Semua itu untuk produk yang disetujui antara anggota koperasi untuk ditanam di tanah tersebut. Dengan sistem ini, petani yang bekerja—sekitar enam orang, Irene salah satunya—mendapatkan kepastian gaji per bulan.
Uniknya dari sistem ini adalah konsumen membayar di muka sebesar 1.400 Franc Swiss (sekitar Rp13,2 juta) per tahun. Semua itu untuk produk yang disetujui antara anggota koperasi untuk ditanam di tanah tersebut. Dengan sistem ini, petani yang bekerja—sekitar enam orang, Irene salah satunya—mendapatkan kepastian gaji per bulan.
Produk pangan yang dihasilkan resikonya ditanggung bersama. Jika produksi berlimpah, konsumen mendapat banyak. Jika produksi susut seperti musim dingin, konsumen juga mendapat sedikit. Seluruh produk dikemas dalam keranjang dan didistribusikan koperasi dalam setiap minggu ke titik-titik pengambilan (drop points) di kota Jenewa.
Konsumen secara mandiri mengambil keranjang bagian mereka. Konsumen juga diwajibkan bekerja di atas lahan selama 16 jam per tahun. “Perlu konsumen yang tercerahkan untuk menjadi bagian sistem ini,” ujar Irene.
Dia juga menyatakan saat ini banyak keluarga di Jenewa yang ingin menjadi bagian koperasi gaya baru ini. Namun untuk kendali mutu dan keterbatasan produksi di tanah sempit tersebut, mereka dengan terpaksa menolak. Saat ini ada puluhan koperasi yang mengadopsi sistem consumer supported agriculture di Swiss.
Di Jardin du Chorroton, hampir seluruh tata kelola sudah termekanisasi. Mereka punya hampir sepuluh rumah kaca dengan konstruksi yang cukup baik, lengkap dengan sistem irigasi. Mereka punya bermacam alat mulai dari traktor tangan hingga traktor besar, mesin-mesin untuk membajak, menggemburkan tanah, membentuk bedeng untuk penanaman benih, dan sebagainya.
Karena bertani dengan sistem pertanian berkelanjutan, proses mengangkat kompos (dan juga proses limbah) juga cukup termekanisasi. “Salah satu teman saya yang bekerja di sini agak tergila-gila dengan mesin,” kata Irene sambil terkekeh.
Salah satu budaya tradisional yang mereka pertahankan adalah kereta yang ditarik kuda. Mereka punya beberapa ekor kuda yang mereka pelihara untuk bekerja di lahan. Mereka bisa membajak, mengangkat hasil pertanian, bahkan untuk demonstrasi. Dari situ nama Chorroton (kereta kuda) berasal.
 Siang itu tampak satu orang konsumen sedang memetik daun saige (sejenis tanaman herbal) dan bekerja di sebidang tanah. Biasanya di akhir minggu, para konsumen mengajak keluarga mereka, terutama anak-anak untuk belajar dan bermain di Jardin du Chorroton.
Siang itu tampak satu orang konsumen sedang memetik daun saige (sejenis tanaman herbal) dan bekerja di sebidang tanah. Biasanya di akhir minggu, para konsumen mengajak keluarga mereka, terutama anak-anak untuk belajar dan bermain di Jardin du Chorroton.
Pola koperasi produksi dan konsumsi pangan seperti ini memang sedang berkembang di seluruh dunia. Jika kita lihat selain Swiss, Jepang, Amerika Serikat dan Spanyol adalah beberapa negara dimana Community Supported Agriculture sedang naik daun. Jika dirata-rata, harga yang didapat tak berbeda jauh dengan pasar konvensional. Nilai lebihnya adalah penekanan pada produk lokal, konsumen tahu kendali mutu, dan pendeknya rantai dagang.
Di sisi petani, selain harga yang terjamin mereka juga meraih pendapatan yang cukup dari sistem tersebut. Petani juga aman dari resiko gagal panen atau turun-naiknya harga.
Bisakah sistem seperti ini dikembangkan di organisasi petani lokal? Dan di Indonesia secara luas?
Penulis adalah Ketua Departemen Luar Negeri Serikat Petani Indonesia. Tulisan ini dibuat di sela-sela aktivitas mengusung hak asasi petani di tengah sidang ke-16 Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa, di Swiss, Maret 2011.