Kerja politik dan propaganda lewat karya seni adalah reproduksi ideologi.
Decak kagum terlontar dari mulut saya ketika pertama kali memegang buku “Taring Padi Seni Membongkar Tirani” kiriman dari Jogjakarta. Wujud buku yang berkesan, sampulnya dari bahan kain blacu bungkus tepung dan isinya dicetak dengan kertas daur ulang.
Sampul buku dicetak dengan teknik cukil kayu (wood cut) yang merupakan karakter menonjol dari poster atau banner yang diproduksi Taring Padi. Teknik cukil kayu menunjukkan Taring Padi ingin mewarisi semangat kerakyatan seniman Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra). Cukil kayu memudahkan reproduksi karya seni sehingga efektif untuk tujuan propaganda.
Harga jual buku yang di atas Rp200 ribu ini bisa kontras dengan citra Taring Padi sebagai kolektif seniman yang mengusung ide-ide kerakyatan, anarkisme, dan seni untuk perubahan. Karena harganya, buku ini akan sulit terjangkau oleh rakyat biasa. Tapi kerja budaya dan kerja politik Taring Padi masih berjalan, masih ada peluang untuk menyebarkan gagasan dalam buku ini dengan lebih murah.
Buku ini dimaksudkan untuk menandai 10 tahun usia Lembaga Budaya Kerakyatan Taring Padi, meski terbit setelah 13 tahun. Reproduksi karya kolektif seperti poster, banner atau mural yang tercecer dikumpulkan dengan susah payah untuk dimuat di buku ini.
Buku ini tidak bertendensi menjadi artifak puja-puji pada kekaryaan Taring Padi dan romantisisme pada gerakan kerakyatan. Ada 12 artikel di buku ini yang sebagian mengkritisi konstruksi makna pada karya rupa Taring Padi. Analisa kritis menambah bobot buku ini, menjadi penyeimbang bagi tampilan reproduksi karya Taring Padi yang memikat secara visual.
Wulan Dirgantoro, misalnya mengkritik cara Taring Padi mengkonstruksi citra perempuan yang berwatak ibuisme, seperti penggambaran perempuan berkebaya. Taring Padi tidak membongkar ideologi patriarki yang pernah dimanfaatkan Orde Baru untuk memelihara kekuasaan tirannya. Tanpa sadar, Taring Padi mereproduksi figur dengan cara yang sama dilakukan oleh rezim yang mereka lawan.
Antimiliterisme juga wacana langganan Taring Padi. Namun dalam mengkritik, Taring Padi menyempit ke militer, bukan militerisme yang sesungguhnya. Sejak Orde Baru tumbang dan Dwi Fungsi TNI dilucuti, justru kian banyak kelompok sipil dengan sifat militeristik, terutama underbouw partai politik dan organisasi massa.
Tak kalah menarik dalam buku ini, ada pembahasan tentang penggunaan jargon-jargon yang cenderung stereotip seperti dalam poster bertema konflik horisontal. Konflik SARA yang melejit pasca Orde Baru tumbang menunjukkan rezim itu telah gagal menanam imajinasi kerukunan. Ada poster Taring Padi dengan teks slogan kebangsaan yang banal seperti “Bangun kebersamaan dalam perbedaan” atau “Bersatu dalam perbedaan”. Persatuan adalah pernyataan semu yang pernah dipelihara lama, sementara banyak tesis menunjukkan konflik horisontal dipicu oleh ketidakadilan eknonomi.
Slogan “Bangun Nusantara tanpa tetes darah” juga terlihat seperti terjebak pada ideologi pembangunan ala Orde Baru. Ini agak mencolok dengan salah satu dari Lima Iblis Budaya yang dilawan Taring Padi sebagai manifesto pendiriannya pada 12 Desember 1998. Lima Iblis Budaya itu adalah individu atau lembaga yang menitikberatkan pada seni untuk seni, yang mensosialisasikan doktrin sesat untuk mempertahankan status quo, pemerintah, yang menjadikan seni sebagai komoditi, lembaga seni yang menjadi legimitator kesenian, sistem yang merusak moral pekerja seni karena melupakan seni dalam masyarakat akibat politik orde baru yang menjadikan ekonomi sebagai panglima.
Muhidin M Dahlan, kepala riset Gelaran Almanak Seni Rupa Jogja 1999-2009 mencatat bagaimana para pelaku seni kerakyatan Taring Padi kompromi dengan galeri-galeri komersial. Surya Wirawan pada Desember 2008 menggelar pameran tunggal di Kedai Kebun Forum Jogjakarta (saudara sepupu Cemeti Art House yang dikecam Taring Padi habis-habisan sebagai salah satu iblis budaya). Arya Pandjalu tidak hanya berpameran di galeri komersial, tapi juga ikut dalam program residensi Landing Soon #1 yang diselenggarakan Cemeti Art House yang bekerja sama dengan Heden, Den Haag di Belanda, November 2006 hingga Januari 2007.
 Presiden pertama Taring Padi Yustoni Volunteero pada Juni 2008 menggelar 17 karyanya di Galeri Biasa. Galeri di Jogjakarta ini menurut Muhidin sama sekali tak punya rekam jejak mengongkosi gerakan-gerakan petani melawan angkara imperialisme global dengan jalan seni rupa.
Presiden pertama Taring Padi Yustoni Volunteero pada Juni 2008 menggelar 17 karyanya di Galeri Biasa. Galeri di Jogjakarta ini menurut Muhidin sama sekali tak punya rekam jejak mengongkosi gerakan-gerakan petani melawan angkara imperialisme global dengan jalan seni rupa.
Gejala itu adalah tantangan terbesar Taring Padi sebagai kolektif seni yang menekan individualisme seniman sebagai cara melawan pola kapitalisme di industri seni. Pertanyaan berikutnya, seberapa besar perolehan para seniman Taring Padi dari pameran untuk mengongkosi hidup gerakan kolektifnya. Bukan tak mungkin, mereka bisa semakin terseret ke pola seni sebagai komoditas yang mengisolasi karya seni di balik tembok galeri atau rumah para kolektor. Toh, kekirian bisa terlihat seksi dan laris.
Taring Padi, Akarumput.com dan Taman 65 bekerja sama menggelar diskusi buku “Taring Padi Seni Membongkar Tirani”. Sebelum diskusi, akan diadakan workshop cukil kayu (wood cut) bersama Taring Padi dan Komunitas Pojok. Dua band asal Bali, Geekssmile dan Navicula, juga akan menunjukkan taringnya dalam format akustik.
Tempat: Taman 65, Jl WR Supratman, Kesiman, Denpasar
Waktu: Sabtu 8 Oktober 2011, jam 15.30 WITA
Partisipan workshop disarankan untuk membawa kaos (T’shirt) polos berwarna cerah untuk disablon dengan teknik cukil kayu. Taring Padi juga menyediakan buku untuk dijual.


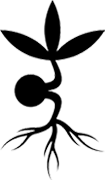










Pingback: Taring Padi’s book launch in Bali | | AkarumputAkarumput