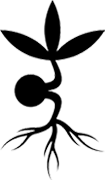Manusia punya hasrat alami untuk menguasai informasi atau pengetahuan lebih cepat daripada manusia lainnya. Hasrat ini yang dikelola oleh industri informasi seperti media massa. Sehingga medan perang teknologi informasi media adalah berlomba cepat mengabarkan.
Manusia punya hasrat alami untuk menguasai informasi atau pengetahuan lebih cepat daripada manusia lainnya. Hasrat ini yang dikelola oleh industri informasi seperti media massa. Sehingga medan perang teknologi informasi media adalah berlomba cepat mengabarkan.
Kenapa manusia ingin lebih tahu atau lebih cepat tahu daripada sesamanya? Karena dengan begitu dia merasa berkuasa atas orang yang belum tahu. Berbagi pengetahuan menjadi sebentuk penundukan. Kekuasaan bukan lagi bagian inheren dan didominasi subjek yang otoritatif seperti negara. Kekuasaan bisa ada dimana-mana, tidak selamanya bersifat represif. Pengetahuan adalah kuasa.
Salah satu bentuk klaim kuasa pengetahuan adalah penjelajahan atau minimal pelancongan, ke tempat-tempat asing. Di Indonesia akhir-akhir ini, tulisan perjalanan (travel writing) berkembang pesat. Begitu banyak buku bertema kisah perjalanan diterbitkan dan menjadi kategori baru di toko buku.
Pesawat terbang bukan lagi moda transportasi yang mahal untuk diakses. Seperti slogan sebuah maskapai penerbangan murah, sekarang semua orang bisa terbang. Turisme juga terus didongkrak sebagai industri. Saat ini 8 persen produk domestik bruto dunia berasal dari industri pelancongan. Tempat mana di dunia ini yang belum dijelajahi manusia. Pelosok dunia yang citra-citranya mengisi halaman media massa sewaktu-waktu bisa menjadi destinasi wisata paling diincar.
Komodifikasi petualangan sebagai gaya hidup menghadirkan hiperealitas tentang tempat-tempat baru yang menantang untuk ditundukkan. Sementara itu dampak degradasi ekologi, budaya dan pergeseran sikap sosial masyarakat setempat, menjadi konsekwensi logis dari kehadiran turisme.
Belakangan ini sedang gencar dipromosikan pemahaman responsible travel. Setiap pelancong harus menyadari apa dampak kehadirannya pada tempat yang ia datangi, baik secara kultural maupun ekologi. Bentuk perjalanan yang paling bertanggung jawab adalah dengan tidak melakukan perjalanan. Karena kehadiran manusia baru di suatu tempat selain bisa menguntungkan, juga bisa menjadi racun.
Hasrat melancong dan membagikan kisah perjalanan menemukan saluran yang tepat dengan adanya media jaringan sosial seperti facebook atau twitter. Seperti dua hari lalu, seorang warga negara Indonesia membagikan foto-foto dan kisahnya melancong ke Tibet lewat akun twitternya.
Ada kepingan cerita maksimal 140 karakter yang umum tentang Tibet itu memuat kekeliruan informasi. Dia menyebut Dalai Lama sudah tidak tinggal di Tibet sejak tahun 1995. Padahal tahun sebenarnya 1959, dan pemimpin spiritual itu bukan sekadar “tidak tinggal” tapi mengungsi ke Dharmsala, India.
Dia juga bercerita tentang istana Potala dan Norbulingka, juga foto-foto panoramanya yang memikat secara visual. Tapi dia lupa bercerita tentang kondisi para rahib di Potala yang jumlahnya tinggal segelintir dan posisi mereka seperti petugas kebersihan dengan seragam (bukan berjubah khas rahib). Dia juga mengingatkan waktu terbaik ke Tibet pada bulan Agustus, September, April dan Mei, saat dia sedang berada di Tibet pada bulan Januari.
Lalu @tibettruth menyebutkan akun itu sebagai turis yang menyebarkan ilusi propaganda China tentang Tibet yang terjajah. @tibettruth adalah akun gerakan internasional yang menghimpun simpat bagi perjuangan kemerdekaan Tibet. Warga Indonesia pelancong itu membalas kalau dia tidak sedang menyebarkan propaganda, intensinya hanya membagikan apa yang dia lihat dan rasakan ke teman-temannya. Respons itu menunjukkan kegagalan menangkap realitas yang telanjang tentang Tibet sebagai tanah terjajah. Padahal di Lhasa setiap 100 meter ada pos tentara China dan mereka tidak berhenti patroli.
Sekitar setahun silam, fotografer Timur Angin melakukan hal serupa lewat twitter. Beberapa saat setelah dari Tibet, Timur mempromosikan rencananya membentuk kelompok tur bersama sebuah majalah fotografi ke Tibet pada bulan terbaik melancong ke Tibet. Rencana ini kandas, karena selama 2011 China tidak mengeluarkan izin masuk [permit] bagi warga asing untuk melancong ke wilayah aneksasi yang disebut Tibet Autonomous Region.
Saya pernah ke Tibet selama 15 hari. Saya menyaksikan Tibet menjadi halaman belakang bagi China yang membutuhkan lokasi piknik bagi warganya yang sedang menikmati lonjakan pertumbuhan ekonomi terbesar di dunia. Saya menyaksikan raut wajah kusam para rahib di kuil atau istana yang dibatasi geraknya pasca aksi perlawanan tahun 2008 yang berujung represi tentara China.
Saya menyaksikan, sektor ekonomi di wilayah Tibet yang dikuasi warga dari daratan China. Hampir seluruh toko souvenir dan kebutuhan turis di Lhasa milik orang China. Orang Tibet yang bahasa Inggrisnya lebih mudah dipahami daripada orang China cukup puas berjualan souvenir di kaki lima Barkhor. Pedagang kaki lima di sana selalu jujur menunjukkan mana barang otentik buatan orang Tibet dan mana souvenir buatan China yang sebenarnya kentara seperti barang China pada umumnya.
Saya menyaksikan jalur kereta ke yang diklaim China sebagai infrastruktur untuk kemajuan Tibet, sebagai moda untuk memobilisasi orang China ke Tibet. Dari penguasaan ekonomi, ruang gerak orang Tibet asli akan kian dikekang. Upaya menancapkan kuku dengan memobilisasi warga di wilayah aneksasi merupakan pengulangan dari yang dilakukan China di Uyghur. Bahkan di Uyghur yang pribuminya mayoritas muslim terjadi upaya pembersihan etnis (ethnic cleansing).
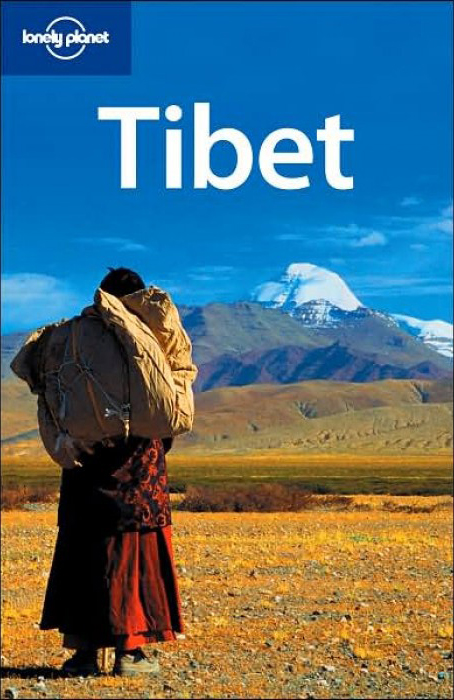 Saya menyaksikan tentara China menahan buku Lonely Planet Tibet yang digeledah dari ransel seorang turis di pos perbatasan dengan Nepal. China mengharamkan Lonely Planet masuk Tibet karena buku panduan itu memuat peta wilayah Tibet dengan warna terpisah dari China dan foto Dalai Lama yang eksil di India.
Saya menyaksikan tentara China menahan buku Lonely Planet Tibet yang digeledah dari ransel seorang turis di pos perbatasan dengan Nepal. China mengharamkan Lonely Planet masuk Tibet karena buku panduan itu memuat peta wilayah Tibet dengan warna terpisah dari China dan foto Dalai Lama yang eksil di India.
Saya menyadari perjalanan saya ke Tibet sebuah kekeliruan. Berwisata ke sebuah wilayah yang terjajah berarti menyalurkan devisa bagi penjajah. Meski di awal perjalanan saya sudah berusaha menekan dampak itu dengan memakai biro perjalanan milik orang Tibet asli, bukan perusahaan China.
Satu-satunya kebanggaan tentang Tibet yang saya simpan adalah kaos dengan bendera dan teks “Free Tibet”. Itupun saya dapatkan di Kathmandu, Nepal, setelah membujuk pedagang kaos untuk membordir simbol legendaris itu. Bendera “Free Tibet” memang populer di Nepal, tapi tidak satu pun pedagang yang berani menyimpan stoknya di toko mereka. Mereka membuat bila ada yang memesan, untuk terhindar dari resiko razia aparat pemerintah Nepal yang sesekali ingin menunjukkan persahabatannya ke China.
Saya menulis beberapa kisah, membuat ribuan foto dan dan puluhan gambar video di Tibet. Tapi saya tidak menyebarkan kisah dan dokumentasi itu sebagai portofolio kebanggaan. Saya tidak ingin menyebarkan pengalaman ke Tibet secara luas sehingga membuat orang lain jadi ingin ke Tibet. Salah satu tulisan saya tentang Tibet saya sematkan menjadi sub judul tulisan ini.
Penjara di Atap Dunia
Di dalam pesawat yang menjelang mendarat, sambutan bentangan alam Tibet membuat mata tak kuasa berkedip. Everest dan puncak-puncak satelitnya seperti pulau di laut awan, menjulang ke langit biru kobal. Salju bertiup seperti bendera yang berkibar dari kejauhan.
Pemandangan yang tak mungkin ditemui di negeri lain. Negeri ini memang atap dunia. Negeri yang sangat istimewa, dengan sejarahnya berselimut tebal spiritualitas, devosi pada Buddha, invasi, penundukan dan penindasan. Negeri yang menjadi mimpi para petualang. Namun mereka harus menghadapi syarat masuk yang cukup ketat, tapi sangat mudah bagi ribuan turis China yang datang setiap musim panas. Tibet ibarat “taman bermain di pekarangan rumah” China.
Dengan pemandu wisata yang menjelaskan dengan perspektif penguasa Tibet, para turis China memenuhi kuil dan biara. Mereka terpesona, dan seharusnya mereka akan lebih terpesona kalau saja tentara China tidak menghancurkan sekitar 6000 biara ketika mengokupasi Tibet tahun 1951. Identitas religius Tibet dilucuti secara brutal ketika itu, dan ribuan orang sipil terbunuh.
Tahun 1959, Tenzin Gyatso, Dalai Lama ke-14, “sang Buddha yang hidup”, meninggalkan Lhasa dan mengungsi ke India untuk meneruskan perjuangan pembebasan tanah airnya.
Di sejumlah kuil dan biara terpajang lengkap lukisan atau foto semua Dalai Lama, kecuali yang ke-14. Sosok itu sangat diharamkan untuk dibicarakan atau terpajang fotonya di Tibet. Pemandu wisata pun dilarang bicara tentangnya. Turis juga dilarang membawa Lonely Planet masuk atau keluar dari Tibet. Sebab “buku suci” para petualang itu memuat foto Dalai Lama dan peta Tibet sebagai negara yang terpisah dari China. China mewajibkan pemakaian istilah Tibet Autonomous Region (TAR) atau agar lebih eksotis: Tibetan Plateau.
Di Potala Palace, istana Dalai Lama, para biarawan tidak diperbolehkan memakai jubah merah khas mereka. Mereka memakai seragam seperti pekerja, dan bertugas seperti di museum. Sejak aksi protes para biarawan tahun 2008 yang berujung pada kekerasan tentara, menjadi biarawan semakin sulit. Jumlah biara pun berkurang drastis. Populasi biarawan di Potala Palace yang sebelumnya sekitar 600 orang, kini tak sampai 200 orang.
Tiket masuk yang cukup mahal ke biara atau kuil semua masuk ke pemerintah China. Kuil dan biara hidup dari derma warga. Karena itu tidak heran di dalam biara, ada peraturan memotret harus bayar, sebagai pemasukan untuk biara. Di Jokhang Temple, biarawan membuka toko dengan plakat “blessed souvernir” Sementara di luar kuil, di Bakhor Square, turis bisa mendapatkan barang yang hampir mirip dengan harga jauh lebih murah.
Di Lhasa, turis bisa didamprat oleh tentara atau polisi China bila memotret pengemis. China khawatir imaji tentang orang miskin akan merusak upaya pencitraan mereka mengenai kemajuan yang terjadi di Tibet. Jalur kereta tertinggi di dunia Qinghai – Lhasa yang beroperasi sejak 2007 diklaim membawa banyak kemajuan bagi Tibet. Padahal jalur kereta api ini justru untuk memudahkan arus barang dari China, juga mobilisasi militer karena China memiliki 3 situs misil nuklir dan penambangan uranium di Tibet.
Seperti juga di Uyghur, China mencengkeram daerah pendudukannya dengan mengontrol komposisi populasi. Semakin banyak suku Han (orang China) di Tibet dan banyak di antara mereka menguasai basis bisnis. Untuk memuluskan asimilasi, orang Tibet dipaksa untuk berbahasa Mandarin lewat sekolah. Sementara tidak ada satupun orang Han yang mau belajar bahasa Tibet.
Saat ini, orang Tibet tidak bisa ke luar negeri karena tidak bisa memiliki paspor. Sampai tiga tahun lalu, masih banyak orang Tibet yang lari ke Nepal melalui pegunungan Himalaya. Namun kini, penjagaan polisi dan tentara China di pegunungan kian ketat. Orang Tibet pun terpenjara di tanahnya sendiri.
“Tibet under lockdown” photo by Ryan Gauvin via Freetibet.org