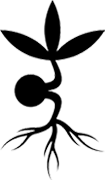Daerah vulkanik di sekitar Danau Batur yang seharusnya subur terus mengalami degradasi lingkungan. Tegal Matanai ingin mengembalikan praktik pertanian yang tidak mengandalkan bahan kimia.
Itu Januari 2007 ketika kali pertama saya menginjakkan kaki di Songan. Apa yang saya rasakan saat itu mungkin sama seperti yang dialami Sutan Takdir Alisjahbana (STA) ketika sampai di desa ini 50 tahun silam. Seperti perasaan antara Yasin dan Molek, tokoh roman karya STA -Dian yang Tak Kunjung Padam. Jatuh cinta.
Jauh dari kesan turistik, desa ini memiliki segalanya yang dibutuhkan untuk hidup di hari ini dan masa depan. Bentang alam yang menakjubkan, ladang-ladang pertanian yang terhampar, pemandian air panas, hingga titik-titik penyelaman air dingin yang sulit ditemukan di penjuru pulau tropis Bali. Sempurna.
Alam seakan mencukupkan segala yang dibutuhkan masyarakatnya hingga tak perlu mengkhawatirkan kondisi geografis desa yang terpencil dan sulit dijangkau. Letak desa di dataran tinggi vulkanik beriklim pegunungan yang sejuk membuat Songan menjadi ladang subur bagi tanaman buah dan sayuran. Hasil pertanian masyarakat setempat menjadi salah satu sumber pasokan ke pasar-pasar di Bali.
Sejak pertama kali ke Songan, saya kerap melewati akhir pekan di sana. Menghabiskan waktu berjam-jam untuk menyusuri perbukitan kecilnya, bermain di danau, berjalan-jalan di desa atau sekadar duduk-duduk menengok ruang buku sang pujangga. Ya, di pintu masuk desa ada rumah peninggalan STA. Pada tahun 1971, STA mendirikan Balai Seni Toyabungkah di sana. Sutan Takdir Alisjahbana pernah memimpikan desa ini akan menjadi pusat seni di masa depan.
Setelah empat tahun, kebiasaan saya ke Songan pun mulai berkurang. Rasanya berkendara selama hampir dua jam dari Denpasar menuju desa mulai terasa tak setara dengan apa yang dilihat. Songan hari ini sudah tak lagi seindah dulu, yang dipicu oleh pergeseran budaya hidup masyarakat yang tak lagi berkaca pada kearifan klasik.
 Saya memerhatikan cara mereka bercocok tanam. Tak kurang dari 50 hektar areal perkebunan buah dan sayur terbentang di Songan. Namun, masyarakat lokal kian meninggalkan sistem pertanian hayati dan mengandalkan bahan kimia untuk mendongkrak hasil. Hasilnya, kuantitas produk memang meningkat. Tapi tanah dan petani sangat bergantung pada bahan kimia pertanian.
Saya memerhatikan cara mereka bercocok tanam. Tak kurang dari 50 hektar areal perkebunan buah dan sayur terbentang di Songan. Namun, masyarakat lokal kian meninggalkan sistem pertanian hayati dan mengandalkan bahan kimia untuk mendongkrak hasil. Hasilnya, kuantitas produk memang meningkat. Tapi tanah dan petani sangat bergantung pada bahan kimia pertanian.
Danau Batur hari ini juga sudah dihapus dari daftar referensi lokasi penyelaman air dingin di Bali. Tengah tahun lalu bersama beberapa penyelam, saya menderita panas dingin dan gatal-gatal selepas melakukan aktivitas penyelaman disana. Saat itu terjadi, masyarakat setempat mengganggap kami mendapat ‘gangguan’ dari penjaga Danau.
Akhirnya muncul gurauan di antara kami jika sebenarnya penjaga danau baik-baik saja andai bahan kimia dari lahan pertanian dan sampah di sepanjang tepian danau tak separah hari ini. Sepertinya karena penduduk telah ‘mengganggu’ penjaga danau maka penjaga danau mulai ‘mengganggu’ kami. Hari itu menjadi kali terakhir kami menyelam di sana.
Di akhir November lalu saya sempat menanyakan penyebab petak-petak kebun sayur yang hancur tersebar di sejauh mata memandang. “Musim hujan, matanai (matahari) jarang muncul, mendung setiap hari,” kata Ketut Sidarta dari tengah kebun sambil memompa tabung berisi cairan bahan kimia yang digendongnya.
 Hanya itu. Ketika panel gagal, alam menolak menjadi tempat tumbuh, terkadang manusia cenderung akan menyalahkan alam. Ketut Sidarta hanya satu contoh petani Songan yang menjadi korban dari sistem pertanian modern. Padahal sistem pertanian yang baik bisa meningkatkan daya tahan tanaman terhadap kondisi cuaca ekstrim sekalipun. Ketut belum tahu jika sistem pertanian yang baik bisa membantunya terhindar dari kerugian gagal panen akibat cuaca.
Hanya itu. Ketika panel gagal, alam menolak menjadi tempat tumbuh, terkadang manusia cenderung akan menyalahkan alam. Ketut Sidarta hanya satu contoh petani Songan yang menjadi korban dari sistem pertanian modern. Padahal sistem pertanian yang baik bisa meningkatkan daya tahan tanaman terhadap kondisi cuaca ekstrim sekalipun. Ketut belum tahu jika sistem pertanian yang baik bisa membantunya terhindar dari kerugian gagal panen akibat cuaca.
Adakalanya manusia lupa akan apa yang pernah diajarkan alam di masa sebelumnya. Seperti masyarakat Songan yang pernah bercocok tanam tanpa melibatkan pupuk produksi pabrik dan insektisida. Dan itu terjadi selama ratusan tahun lamanya.
Tanah yang sehat menjadi tempat hidup dan berkembang mikroorganisme yang menguntungkan, di antaranya biota yang bisa menjadi antibiotik untuk melindungi tanaman dari hama penyakit. Beberapa organisme lain akan memproduksi makanan alami bagi tanaman sementara yang lainnya menjaga unsur hara tanah. Penggunaan pupuk dan insektisida telah memutus mata rantai itu. Tanaman dipaksa tumbuh dengan bahan-bahan kimia sementara tempat mereka mengakar miskin sudah dari kandungan nutrisi alami. Di Songan, petani seakan memaksa tanaman dan alam bekerja untuk mereka, bukan sebaliknya. Saya melihat Songan cikal desa mandiri yang terpinggirkan.
Apa yang terjadi di Songan hari ini bukan semata tentang merosotnya kualitas lingkungan. Di sana kearifan lokal terkikis sudah akibat pola hidup yang kelewat konsumtif dan tak berwawasan masa depan. Padahal Songan memiliki segala yang dibutuhkan untuk menjadi sebuah desa mandiri.
 Asa untuk perubahan mulai terpercik. Beberapa proyek lingkungan berskala kecil terkait pertanian sehat mulai digagas di sana. Salah satunya Tegal Matanai, diambil dari bahasa setempat yang berarti Kebun Matahari. Berlokasi di Banjar Serongga, sepetak tanah garapan milik pemangku desa digarap secara kolaboratif oleh beberapa praktisi pertanian dengan merangkul anak-anak sekolah setempat. Tegal Matanai akan sepenuhnya digarap dengan berkiblat pada kearifan lokal. Semua yang terlibat dalam proyek sederhana ini mengajak setiap orang untuk hidup bersanding dengan alam, dan untuk alam.
Asa untuk perubahan mulai terpercik. Beberapa proyek lingkungan berskala kecil terkait pertanian sehat mulai digagas di sana. Salah satunya Tegal Matanai, diambil dari bahasa setempat yang berarti Kebun Matahari. Berlokasi di Banjar Serongga, sepetak tanah garapan milik pemangku desa digarap secara kolaboratif oleh beberapa praktisi pertanian dengan merangkul anak-anak sekolah setempat. Tegal Matanai akan sepenuhnya digarap dengan berkiblat pada kearifan lokal. Semua yang terlibat dalam proyek sederhana ini mengajak setiap orang untuk hidup bersanding dengan alam, dan untuk alam.
Tegal Matanai akan mencoba tumbuh dengan cara yang berbeda dari praktek pertanian yang umum berlaku di Songan. Selain menyemai benih buah, sayuran dan bunga matahari, proyek ini menanam benih harapan.
Semoga perlahan masyarakat setempat tersadarkan, ada yang jauh lebih penting dari hidup cukup di hari ini. Semoga Tegal Matanai bisa menjadi dian atau cahaya yang menghangatkan harapan. Agar Songan laksana dian yang tak kunjung padam.
Foto oleh Teddy Drew.